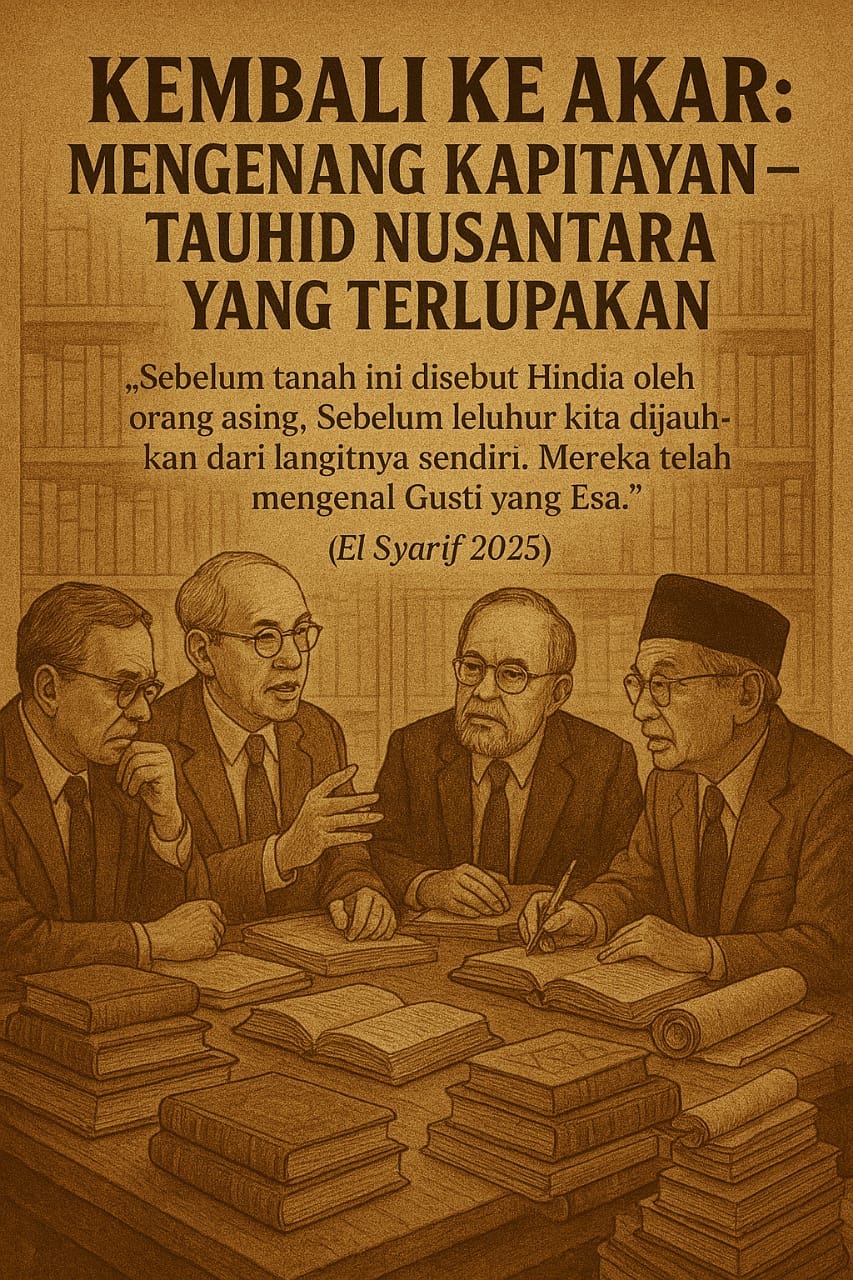Sebuah tafsir berbasis Sain dari Surah Al-Kahf ayat ke-96, ayat yang menceritakan langkah strategis Zulkarnain dalam membendung Ya’juj dan Ma’juj:
اٰتُوۡنِىۡ زُبَرَ الۡحَدِيۡدِ ؕ حَتّٰٓى اِذَا سَاوٰى بَيۡنَ الصَّدَفَيۡنِ قَالَ انْـفُخُوۡا ؕ حَتّٰٓى اِذَا جَعَلَهٗ نَارًا ۙ قَالَ اٰتُوۡنِىۡۤ اُفۡرِغۡ عَلَيۡهِ قِطۡرًا
Artinya:
“Berilah aku potongan-potongan besi!” Hingga ketika (potongan) besi itu telah (terpasang) sama rata dengan kedua (puncak) gunung itu, dia (Zulkarnain) berkata, “Tiuplah (api itu)!” Ketika (besi) itu sudah menjadi (merah seperti) api, dia pun berkata, “Berilah aku tembaga (yang mendidih) agar kutuangkan ke atasnya (besi panas itu).”
Banyak ulama menafsirkan “qithr” sebagai tembaga, namun DR. Ary menggulirkan tafsir teknologis, bahwa ‘qithr’ bukanlah sekadar tembaga, melainkan kuningan, alloy dari tembaga dan seng, yang dalam dunia metalurgi dikenal karena daya tahannya terhadap karat dan kemudahan pembentukannya. Ketika kuningan dikombinasikan dengan sedikit besi, akan tercipta logam magnetik yang bukan hanya kuat secara fisik tapi juga strategis. Pintu logam hasil alkimia Zulkarnain itu bukan hanya penghalang material, tapi juga alat pertahanan sains, yakni menarik senjata logam, membuat musuh kehilangan daya serang. Inilah tembok peradaban. Sebuah kemajuan yang tak hanya melibatkan otot dan logam, tetapi juga logika dan ilham dari langit.
“Allah mengajarkan kepada Zulkarnain ilmu metalurgi,” ujar DR. Ary.
Bukan berlebihan jika ini disandingkan dengan nama besar Jābir ibn Hayyān, sang Bapak Kimia, yang dikenal di Barat sebagai Geber. Jābir merumuskan teori tentang logam, alkimia, dan struktur materi jauh sebelum ilmuwan Eropa mengenal tabel periodik. Di tangan Zulkarnain dan Jābir, sains bukanlah barang yang asing lagi.
Menurut DR. Ary Kiem:
“Falaq + Matematika = Mantiq (Logika). Logika + Rasa = Sastra. Sastra itu memanusiakan manusia.”
Pernyataan itu mengingatkan kita bahwa sains, logika, dan sastra tidak boleh tercerabut satu sama lain. Sebab ketika ilmu tanpa rasa, maka lahirlah teknokrasi dingin. Ketika rasa tanpa logika, maka menjelmalah khurafat dan tahayul. Dan ketika sastra tercerabut dari wahyu, maka kata-kata kehilangan arah.
Dan sastra tertinggi adalah wahyu. Al-Qur’an, kitab yang diturunkan dengan tujuh dialek, tujuh cita rasa, tujuh lapisan makna. Dialah teks suci yang merangkum logika dan rasa, mengikat langit dan bumi dengan kata.
Ketika DR. Ary berkata, “Saya mungkin cucunya Musa AS yang bertemu dengan cucunya Keturah, putri Syu’aib AS,” ia bukan hanya sedang bersastra, tetapi sedang mewartakan tafsir baru tentang takdir dan pertemuan peradaban. Ia mengaitkan Batak dan Israel Kuno, keris Majapahit dan gerbang Zulkarnain, dengan narasi besar kemanusiaan.
“Allah menjaga dan melindungi dengan SAINS. Allah berbicara pada manusia dengan bahasa sains.”
Inilah epistemologi tauhid yang memanusiakan manusia, bukan dari jubah, titel, atau sorban, tapi dari rasa ingin tahu, keberanian berpikir, dan kasih sayang terhadap ilmu.
DR. Ary mengutip kisah Iblis:
“Iblis tidak mau sujud karena sombong. Ia tahu Adam lebih baik, tapi menolak mengakuinya.”
Maka benarlah, bahwa ilmu tanpa rendah hati adalah jalan Iblis. DR. Ary memadukan falaq, logika, dan sastra bisa jadi lebih mulia dari mereka yang bersurban tapi memiskinkan pikirannya. Ini bukan tentang siapa yang suci, tapi siapa yang terus mencari. Bukan tentang siapa yang kaya, tapi siapa yang menyalakan cahaya.
Dan Zulkarnain pun membangun tembok raksasa itu, dengan besi dan logika, dengan api dan sains dan dengan qithr dan rasa. Sebuah peradaban dimulai bukan dari takhta, tapi dari keberanian membaca wahyu dan semesta dengan mata terbuka.
Wallahu a’lam
Sumber:
1. Abdur Rahman El Syarif
2. Dr. Ary Keim
#Islam #Alquran #Hadis #sains #Zulkarnain #peradabanislam #nusantara